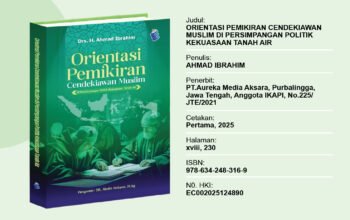Oleh: A. Malik Ibrahim
Adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Politik Bermukim di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
DALAM satu kesempatan, saya pernah berdiskusi dengan Romo Frans Magnis Suseno, S.J. pengajar filsafat dan penulis buku Etika Politik. Baginya, “tanpa etika, kekuasaan akan melorot menjadi sesuatu yang menakutkan”.
Dan sekarang ini, kita hanya dengar kabar buruk dari partai politik. Dalam leksikon demokrasi, partai politik dikenal sebagai a necessary evil, makhluk buruk rupa namun diperlukan. Demokrasi tak bisa hadir tanpa partai politik. Tapi apa, yang kita dengar dari percakapan publik, hanya kekacauan, kebingungan, ketidakpastian, intrik dan rivalitas yang sambung menyambung.
Arah politik berjalan begitu suram dan tidak karuan. Gigantisme partai-partai koalisi tak mampu mengatasi keadaan sosial-politik dan ekonomi. Partai politik seolah bergerak ke tujuan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tapi bagi politikus kekacauan dan kebingungan adalah sumber inspirasi.
Dan demokrasi? Kata Horkheimer, prinsip mayoritas demokrasi kini sudah dilucuti sisi obyektif dan rasionalnya. Ia diganti oleh interest of the people, yang tak lain adalah kekuatan ekonomi buta, yang membungkam akal budi manusia (Sindhunata, 2019 : 162). Dalam politik bahasa sederhana dan lentur justru diperlukan untuk menyampaikan konsep-konsep yang rumit seperti apa itu politikus.
Profesor Antropolinguistik Unkhair, Gufran A. Ibrahim, menulis soal (Poli)-Tikus. “Tulisnya, bisa “(Poli)-Tikus, bisa juga Poli (Tikus). Tergantung kata mana yang dipentingkan, apakah Poli-nya atau Tikus-nya”. Baginya, sekedar tahu saja, kata poli dalam ilmu bahasa disebut morfem terikat (bound morpheme). Ia harus sama dengan kata lain untuk membangun sebuah makna,” (Ibrahim,2004 : 78).
***
Belakangan saya baca politik Algofobia, (Tajudin, 2025:29). Apa pula algofobia ini? Perdefinisi algofobia adalah ketakutan umum terhadap rasa sakit. Sebuah pergulatan ketakutan yang kuat dan tidak rasional pada kesakitan. Semua rasa sakit dihindari, termasuk rasa sakit akibat dikhianati.
Sangat terasa betapa kita terus diajak bergulat dengan algofobia – sakit oleh kecurigaan, termasuk rasa sakit karena konflik politik. Sekaligus, algofobia juga jadi obat bius yang membuat kita tak punya kepekaan. Dalam kondisi seperti ini, jangan berharap pada perubahan radikal dunia politik. Begitulah gaya seorang politikus, ia tidak berpikir tentang “lurus” sebagai lawan “tidak lurus” melainkan sebagai berlawanan dengan “bengkok”, “melengkung”, “zig-zag”, dan sebagainya.
“Transformasi dan kemajuan yang kita nikmati dewasa ini, sebagian besar dibangun atas pundak-pundak jutaan manusia yang menderita”, begitulah tulis Peter L. Berger dalam Pyramids of Sacrifice (1974). Berger menegaskan perlunya hak manusia untuk tidak menderita.
Politik itu warna-warni. Merah, kuning, hijau, biru, pink. Dan warna yang menyolok abu-abu. Mau paham atau tidak, kemenangan adalah segala-galanya. Semua orang bisa masuk ke ranah politik, menjadi politikus.
Tapi, “tak semuanya paham apa itu politik, sebelum atau bahkan ketika sudah memasuki dunia politik. Politik kadang aneh dan susah dipahami. Politik itu candu : kalau sudah terlibat susah berhenti. Politisi merasa tak pernah mati, sehinggaa zoon politicon berlaku selamanya. Menurut Winston Churchill, tentara terbunuh sekali, tetapi politikus bisa berkali-kali. In war, you can only be killed once, but ini politics, many times, (Alfian,2016).
Dalam totalitarianism politik, di mana, “semua masalah adalah masalah politik, dan politik itu sendiri, sindir George Orwel, adalah kebohongan, penggelapan, kebodohan, kebencian dan skizofrenia yang dilakukan secara massif”,(Ibid).
Bangsa ini tengah belajar demokrasi, biayanya mahal. Berbagai peristiwa politik yang tak masuk akal terjadi. Politikus mabuk kemenangan. Mereka berjoget riang sambil membuka mulut lebar-lebar bagaikan orang kemaruk, untuk membuktikan “seolah-olah” mereka mewakili kedaulatan rakyat. Dan pimpinan partai politik jadi inferior — mati kutu karena dikarbit ketiak kekuasaan.
Syekh Muhammad Hisyam Kabbani, pemimpin sufi kosmopolit, mencela demokrasi yang tujuannya dibelokkan dan berubah jadi money-crazy. “Kabbani mengatakan, “sebagian praktik demokrasi saat ini diwarnai politik uang. Siapa punya uang, ia akan menang. Uang beli suara. Ini bukan demokrasi, melainkan money-crazy. Karena akhirnya, mereka tidak menggunakaan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat, (Alfian, hal.465).
“Tapi bagi politikus, “persetan dengan apologi itu. Politik adalah uang, kuasa, reputasi dan penghambaan. Bukan ilusi yang mengawang”.
***
Dengan begitu, tak ada yang menyangkal atas “the leading figure” demokrasi moderen Sidney Hook dan Karl R. Popper. Keduanya dikenal sebagai penganjur dan pembela demokrasi humanisme dalam tradisi pemikiran filsafat yang berbeda. Demokrasi humanistik Sidney Hook mengalir dalam tradisi Pragmatisme. Dan Popper dari tradisi Epistemologi Kritis. Namun, secara geneakologis, berasal dari akar filsafat yang sama; humanisme Socrates. Jelasnya, equality dan equal justice dasar dari etika politik.
Kekuasaan politik apa pun dimensinya, fantasinya adalah seratus persen instink dan naluri (nafsu). Agar kekuasaan tak jadi liar dan buas manusia memerlukan kesadaran nilai etik, semacam oase ruhaniah – meminjam istilah Peter L. Berger, kanopy suci (the sacred canopy).
Tentu, semuanya kembali pada manusia. Lalu, apa pengertian dasar kita tentang manusia.
Apakah itu bios politikos, semacam binatang yang sanggup berpikir atau ens possible, makhluk penuh kemungkinan. Perspektif kualitas manusia sangat tergantung pada antropologi yang kita anut.
Dramatis dan penuh kemungkinan. Jadi, setiap orang adalah gado-gado dari yang baik dan buruk, campuran kimia dari sifat-sifat loyal dan kecenderungan sifat Brutus, rakitan dari roh Bismarck dan psikologi Hamlet, medan pertempuran antara keserakahan dan kesetiaan. Pokoknya, a compound of dust divinity.
Jawabnya jelas, politikus adalah orang yang percaya akan hal itu dan bekerja atas dasar kepercayaan itu. Bagi dia selalu ada kemungkinaan bahwa orang baik dalam hidupnya dapat berubah (dan diubah) jadi penjahat, dan seorang bajingan berubah (dan diubah) jadi tokoh teladan. Dua kemungkinan itu sama besar, dan politikus berusaha mewujudkan kemungkinan kedua.
Sebab, tiap prestasi yang dicapai seorang politikus tetaplah hanya satu kemungkinan – yang pada menit berikutnya dapat disabot kembali oleh unsur-unsur gelap. Setiap detik dalam politik adalah perebutan dan pertarungan.
Jika kita tak punya akal budi, maka kekerdilan adalah sebab mengapa demikian banyak politikus menjadi tak akil balig sedemkian lama dalam partai politik? Tidakkah di sana justru banyak ditontonkan kebenaran, yang bisa jadi cermin hikmah bagi kepura-puraan kita?. (*)